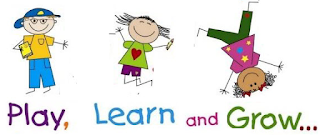Pengertian, Sejarah,Objek, Ciri-ciri, Asal, Manfaat, Kegunaan dan Peranan Filsafat
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Filsafat adalah ratuya ilmu-ilmu, begitu biasanya dia disebut. Filsafat diartikan sebuah disiplin ilmu yang telah berusia ribuan tahun. Sejak dari perkembangan yang paling awal, filsafat tidak pernah lepas dari konteks kultural masyarakat tempat ia tumbuh dan berkembang. Kehadiran filsafat di zaman Yunani kuno dapat dikatakan sebagai langkah awal pembebasan akal manusia dari kultur mitologis yang membelenggu potensi-potensi rasional manusia. Kesangsian, keheranan yang bercampur kekaguman, merupakan titik awal munculnya filsafat. Kesadaran baru bahwa akal manusia memiliki kekuatan yang luar biasa tajam untuk membelah semua dogmatisme dan kepercayaan palsu. Kritis! Itulah kata kunci yang digenggam semua filsuf di sepanjang zaman.
Untuk memahami apa sebenarnya filsafat itu, tentu saja tidak cukup hanya mengetahui asal usul dan arti istilah yang digunakan, melainkan juga harus memperhatikan konsep dan definisi yang diberikan oleh para filsuf menurut pemahaman mereka masing masing. Akan tetapi, perlu pula dikatakan bahwa konsep dan definisi yang diberikan oleh para filsuf itu tidak sama. Bahkan, dapat dikatakan bahwa setiap filsuf memiliki konsep dan membuat definisi yang berbeda dengan filsuf lainnya. Karena itu, ada yang mengatakan bahwa jumlah konsep dan definisi filsafat adalah sebanyak jumlah filsuf itu sendiri.
 |
| makalah filsafat |
Makalah filsafat bermaksud memandu pembaca untuk memperoleh gambaran apakah filsafat itu, sejarahnya, objek-objek dalam filsafat, ciri-ciri filsafat, asal, manfaat, kegunaan, dan peranan filsafat.
2. RUMUSAN MASALAH
- Apa Pengertian Filsafat?
- Bagaimana Sejarah dari Filsafat?
- Apasaja Objek dari Filsafat?
- Bagaimana Ciri-ciri Filsafat?
- Sebutkan Asal Filsafat?
- Apasaja Manfaat Belajar Filsafat?
- Apasaja Kegunaan Belajar Filsafat?
- Bagaimana Peranan Filsafat?
BAB II
FILSAFAT
1. PENGERTIAN FILSAFAT
Pengertian filsafat dapat ditinjau dari dua segi yakni secara etimologi dan terminologi:
1) Pengertian Filsafat Secara Etimologi
Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia. Kata philosophia terdiri atas kata philein yang berarti cinta (love) dan sophia yang berarti kebijaksanaan (wisdom), sehingga secara etimologi istilah filsafat berarti cinta kebijaksanaan (love of wisdom).
Istilah filsafat (philosophia) itu sendiri menunjukkan bahwa manusia tidak pernah secara sempurna memiliki pengertian menyeluruh tentang segala sesuatu yang dimaksudkan kebijaksanaan, namun terus menerus mencarinya. Berkaitan dengan apa yang dilakukannya, filsafat adalah pengetahuan yang dimiliki rasio manusia yang membuat dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu. Filsafat menggumuli seluruh realitas. Jadi, filsafat adalah upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas.
2) Pengertian Filsafat secara Terminologi
Pengertian Filsafat menurut ahli:
Plato
Plato berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli.
Aristoteles
Menurus Aristoteles, filsafat adalah ilmu (pengetahuan) yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika (filsafat keindahan).
Rene Descartes
Menurut Rene Descartes, filsafat adalah kumpulan semua pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan.
Immanuel Kant
Menurut Kant, filsafat adalah ilmu (pengetahuan) yang menjadi pangkal semua pengetahuan yang di dalamnya tercakup masalah epistemology (filsafat pengetahuan) yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui.
N. Driyarkara
Menurut Driyarkara, filsafat adalah perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebab ‘ada dan berbuat’, perenungan tentang kenyataan (reality) yang sedalam-dalamnya sampai ke ‘mengapa’ yang penghabisan.
Jadi, dari batasan-batasan di atas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat adalah ilmu (pengetahuan) yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan menggunakan akal sampai pada hakekatnya.
2. SEJARAH FILSAFAT
1) Sejarah Filsafat Barat
Menurut Surajiyo dalam buku Ilmu Filsafat (2014) sejarah Filsafat Barat dibagi dalam periode Yunani kuno, abad pertengahan, zaman modern, dan masa kini.
1. Zaman Filsafat Yunani Kuno
Zaman kuno meliputi zaman pra-Socrates di Yunani. Tokoh-tokohnya dikenal dengan nama filsuf pertama atau filsuf alam. Mereka mencari unsur induk (arche) yang dianggap asal dari segala sesuatu. Menurut Thales, arche itu air, Anaximandros berpendapat arche itu ‘yang tak terbatas’ (to apeiron). Menurut Anaximenes, arche itu udara, Pythagoras, arche itu bilangan, Heraklitos arche itu api, ia juga berpendapat bahwa segala sesuatu itu terus mengalir (panta rhei). Parmenides mengatakan bahwa segala sesuatu itu tetap tidak bergerak.
2. Zaman Abad Pertengahan
Filsafat pada abad pertengahan mengalami dua periode:
a. Periode Patristik
Patristik berasal dari bahasa Latin patres yang berarti bapa-bapa gereja, ialah ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen.
b. Skolastik. Berlangsung dari tahun 800 M – 1500 M.
3. Zaman Modern
Zaman modern dimulai dari zaman renaissance yang berarti kelahiran kembali, yaitu usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik (Yunani-Romawi). Pembaruan terpenting yang kelihatan dalam filsafat renaissance itu ‘antroposentrisme’nya. Pusat perhatian itu tidak lagi kosmos seperti zaman kuno, atau Tuhan seperti abad pertengahan, melainkan manusia. Mulai zaman modern inilah manusia dianggap sebagai titik focus dari kenyataan.
4. Masa Kini
Masa kini dimulai dari abad ke-19 dan 20. Dengan timbulnya berbagai aliran yang berpengaruh seperti positivism, marxisme, eksistensialisme, pragmatism, neo-kantianisme, neo-thomisme, dan fenomenologi. Aliran-aliran ini sangat terikat oleh keadaan negara maupun lingkungan bahasa sehingga dalam perkembangan terakhir lahirlah filsafat analitis yang lahir sejak tahun 1950.
2. Sejarah Filsafat Timur
Filsafat India
Menurut Rabindranath Tagore (1861-1941), filsafat India berpangkal pada keyakinan bahwa ada kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Harmoni ini harus disadari supaya dunia tidak dialami sebagai tempat keterasingan ataupun sebagai penjara.
Filsafat India bercorak religious dan etis. Sejarah filsafat India dibagi menjadi empat periode, yaitu periode Weda (1500-600 SM), periode Wiracarita (600 SM – 200 SM), periode Sutra-sutra (200 SM – sekarang), periode Skolastik (200 SM – sekarang).
Periode Weda
- Weda Samhita adalah suatu pengumpulan mantra-mantra, yang berbentuk syair yang dipergunakan untuk mengundang dewa, yang untuknya akan dipersembahkan korban, agar ia berkenan menghadiri upaya korban itu, juga untuk menyambut dewa yang diundang tadi, setelah dianggapnya sebagai telah hadir, dan untuk mengubah korban yang dipersembahkan hingga menjadi makanan dewa yang sebenarnya.
- Kitab Brahmana yaitu bagian kedua kitab Weda, berbentuk prosa yang pewahyuannya terjadi setelah zaman mantra-mantra diwahyukan.
- Kitab Upanisad berbentuk prosa dan diwahyukan setelah zaman Brahmana.
Jadi, yang menonjol untuk filsafat India adalah dalam Upanisad, yakni ajaran tentang hubungan antara Atman dan Brahman. Atman adalah segi subyektif dari kenyataan ‘diri’ manusia. Brahman adalah segi obyektif makrokosmos alam semesta.
Periode Wiracarita
Periode ini sering disebut periode epic atau periode hikayat cerita-cerita kepahlawanan. Periode ini meliputi berkembangnya upanisad-upanisad yang tertua dan system filsafat (Darstyana).
Periode Sutra-sutra
Pada periode ini bahan yang berupa konsep-konsep pemikiran menjadi banyak sehingga sukar sekali untuk disederhanakan serta perlu untuk membuat semacam rangkuman, skema kefilsafatan yang pendek dan ringkas. Ikhtisar ini dibuat dalam bentuk suta-sutra.
Periode Skolastik
Pada periode ini, guru-guru filsafat dijumpai berselisih paham karena masing-masing mempunyai teori-teori sendiri yang cukup mantap, dengan mengajukan alasan-alasan yang tersusun rapi (Surajiyo, 2014).
3. OBJEK FILSAFAT
Objek adalah sesuatu yang merupakan bahan dari suatu penelitian atau pembentukan pengetahuan (Surajiyo, 2014). Ada dua obyek filsafat yaitu objek material dan objek formal.
Objek material adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu. Objek formal yaitu sudut pandang yang ditujukan pada bahan dari penelitian atau pmembentukan pengetahuan itu (Surajiyo, 2014).
Jadi, yang membedakan filsafat dengan ilmu-ilmu lain terletak dalam objek material dan objek formalnya. Jika dalam ilmu-ilmu lain, objek materialnya mambatasi dari apapun pada objek formalnya membahas objek materialnya itu sampai ke hakikatnya untuk esensi dari yang dihadapinya.
4. CIRI-CIRI FILSAFAT
1) Berpikir radikal
Berpikir radikal berarti berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Berpikir radikal hendak memperjelas realitas lewat penemuan serta pemahaman akan akar realitas itu sendiri.
2. Mencari asas
Mencari asas pertama berarti berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas. Dengan menemukan esensi suatu realitas, realitas itu dapat diketahui dengan pasti dan jelas.
3. Memburu kebenaran
Kebenaran filsafati tidak pernah bersifat mutlak dan final, melainkan terus bergerak dari suatu kebenaran menuju kebenaran baru yang lebih pasti. Kebenaran yang baru ditemukan itu juga terbuka untuk dipersoalkan kembali, demi menemukan kebenaran yang lebih meyakinkan.
4. Mencari kejelasan
Mengejar kejelasan berarti berjuang untuk mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas, yang kabur, dan yang gelap, bahkan juga serba rahasia dan berupa teka-teki. Berfilsafat sesungguhnya merupakan suatu perjuangan untuk mendapatkan kejelasan pengertian dan kejelasan seluruh realitas.
5. Berpikir rasional
Berpikir rasional adalah berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berpikir logis berarti upaya menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar dari premis-premis yang digunakan. Pemikiran sistematis adalah rangkaian pemikiran yang berhubungan satu sama lain atau saling berkaitan secara logis. Berpikir kritis berarti upaya untuk terus menerus mengevaluasi argumen-argumen yang mengklain diri benar. (Jan Hendrik Rapar, 1995).
5. ASAL FILSAFAT
Ada beberapa hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu sebagai berikut:
1. Ketakjuban.
Ketakjuban hanya mungkin dirasakan dan dialami oleh makhluk yang berperasaan dan berakal budi. Manusia adalah makhluk yang takjub. Objek ketakjuban adalah segala sesuatu yang ada dan yang dapat diamati.
2. Ketidakpuasan
Sebelum filsafat lahir, berbagai mitos dan mite (dongeng dan takhayul) menjelaskan tentang asal mula dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta serta sifat-sifat peristiwa itu. Manusia tidak puas dengan penjelasan itu. manusia terus menerus mencari penjelasan dan keterangan yang lebih pasti itu lambat-lambat mulai berpikir secara rasional. Akibatnya, akal budi semakin berperan. Mitos dan mite tersisih, filsafat lahir.
3. Hasrat bertanya
Ketakjuban manusia telah melahirkan pertanyaan, dan ketidakpuasan manusia membuat pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung habis. Pertanyaanlah yang membuat manusia melakukan pengamatan, penelitian dan penyelidikan.
4. Keraguan
Pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh kejelasan dan keterangan yang pasti pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan tentang adanya keraguan di pihak manusia yang bertanya.
5. Kesadaran akan keterbatasan
Manusia merasa bahwa ia sangat terbatas dan terikat terutama pada waktu mengalami penderitaan atau kegagalan. Dengan kesadaran akan keterbatasan dirinya ini, manusia mulai berfilsafat. Ia mulai memikirkan bahwa di luar manusia yang terbatas pasti ada sesuatu yang tidak terbatas.
6. MANFAAT BELAJAR FILSAFAT
- Menjawab pertanyaan mendasar tentang kehidupan.
- Memeberi alternative penanganan masalah terdalam manusia serta hakikat kebaikan dan kebenaran.
- Merefleksikan pikiran filsuf terdahulu dan mengambil maknanya untuk kehidupan sekarang.
- Mampu berpikir kritis-rasional dan otonom-mandiri.
7. KEGUNAAN FILSAFAT
Kegunaan filasafat adalah sebagai pedoman untuk berpikir, bersikap, dan bertindak secara sadar dalam menghadapi berbagai gejala–peristiwa yang timbul dalam alam dan masyarakat. Untuk berfilsafat, orang harus mengetahui dan memahami ajarannya secara ilmu – mempelajari aliran-aliran filsafat. Berfilsafat berarti bersikap dan bertindak kritis, mencari sebab, mencari isi, mencari hakikat dari gejala–peristiwa alam dan masyarakat, bukan bersikap dan bertindak secara tradisi, kebiasaan, adat-istiadat dan naluri. (Darsono)
Filsafat berguna sebagai penghubung antardisiplin ilmu. Selain itu, filsafat juga sanggup memeriksa, mengevaluasi, mengoreksi, dan lebih menyempurnakan prinsip-prinsip dan asas-asas yang melandasi berbagai ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan praktis, filsafat menggiring manusia ke pengertian yang terang dan pemahaman yang jelas. Kemudian menuntun manusia ke tindakan dan perbuatan yang konkret berdasarkan pengertian yang terang dan pemahaman yang jelas. (Jan Hendrik Rapar, 1995).
Menurut Frans Magnis Suseno, Filsafat berguna untuk membantu mengambil sikap sekaligus terbuka dan kritis menghadapi tantangan modernisasi dengan perubahan pandangan hidup, nilai, dan norma (Surajiyo, 2014).
8. PERANAN FILSAFAT
a. Pendobrak.
Mendobrak tembok-tembok tradisi (dongeng dan takhayul) yang begitu sakral dan selama itu tak boleh diganggu-gugat.
b. Pembebas
Membebaskan manusia dari “penjara” yang hendak mempersempit ruang gerak akal budi manusia.
c. Pembimbing
- Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir mistis dan mitis dengan membimbing manusia untuk berpikir secara rasional.
- Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang picik dan dangkal dengan membimbing manusia untuk berpikir luas dan lebih mendalam (radikal).
- Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir tidak teratur dan tidak jernih dengan membimbing manusia berpikir sistematis dan logis.
- Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang tak utuh dan fragmentaris dengan membimbing manusia untuk berpikir secara integral dan koheren.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Filsafat adalah upaya manusia untuk menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakekatnya. Jadi, dalam filsafat objeknya tidak membatasi diri. Filsafat membahas objeknya sampai kedalamannya, sampai keradikalan dan totalitas. Secara umum, asal filsafat ada tiga hal yakni, keheranan, kesangsian, dan kesadaran akan keterbatasan. Karatkteristik pemikiran filsafat adalah berpikir radikal, mencari asas, memburu kebenaran, mencari kejelasan, dan berpikir rasional.
Pemikiran filsafat banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Di Yunani dengan mitosnya, di India dengan kitabnya, Weda. Di Barat, mitos dapat lenyap sama sekali dan rasio yang menonjol, sedangkan di India, filsafat tidak bisa lepas dengan induknya yaitu agama Hindu.
DAFTAR PUSTAKA
Gahral, Donni Adian. 2011. Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan. Depok: Koekoesan
Hendrik, Jan Rapar. 1995. Pengantar Filsafat. Yogyakarta: Kanisius
Latif, Mukhtar. 2014. Orientasi ke arah Pemahaman Filsafat Ilmu. Jakarta: Kencana
Surajiyo.2008. Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia. Jakarta: PT.Bumi Aksara
Surajiyo. 2014. Ilmu Filsafat Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Bumi Aksara